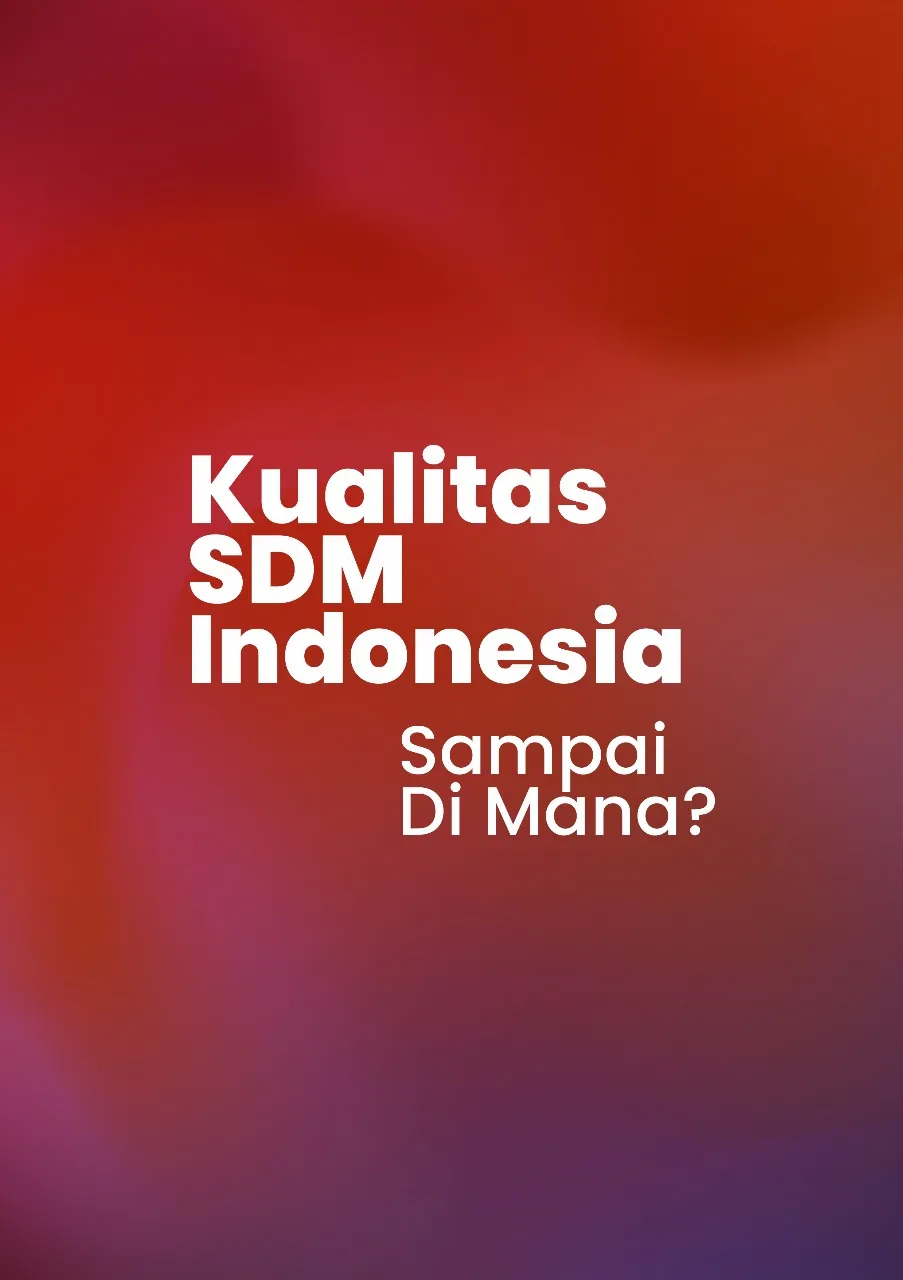Kualitas SDM Indonesia Sampai di Mana?
27 Maret, 2025
Indonesia diperkirakan menghadapi puncak bonus demografi pada 2030. Namun potret kualitas SDM yang ada justru masih mengkhawatirkan.

Keterangan foto: Ilustrasi ruang kelas kosong.
Ringkasan
• Bonus Demografi dan Tantangan SDM
Indonesia sedang berada pada masa bonus demografi yang puncaknya diperkirakan berakhir pada 2030. Meski ini peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM yang rendah dapat menjadi ancaman. Tanpa peningkatan keterampilan dan pembukaan lapangan kerja baru, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
• Kualitas Pendidikan Masih Tertinggal di Asia Tenggara
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal di posisi keenam Asia Tenggara, di bawah Vietnam dan Thailand. Rendahnya rasio lulusan pendidikan tinggi menjadi persoalan serius—hanya 9,33% penduduk usia 25 tahun ke atas yang bergelar S1 atau lebih. Kondisi ini menunjukkan daya saing SDM Indonesia masih lemah dibanding negara tetangga.
• Pendidikan Tinggi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, hanya sekitar separuh lulusan SMA yang melanjutkan ke universitas. Mahalnya biaya kuliah menjadi hambatan utama. Pemerataan akses pendidikan berkualitas dan dukungan pembiayaan menjadi syarat penting agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Cita-cita besar Indonesia Emas 2045 digaungkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Peta jalan telah disusun dan resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Visi besar RPJPN adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan ketika mencapai usia 100 tahun. Satu di antara komponen terpenting untuk mewujudkan visi tersebut adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Keberhasilan pembangunan akan sangat bergantung kepada pikiran dan tangan manusia yang mengerjakannya.
Sebagai sebuah negara yang luas dan berpopulasi besar, SDM bisa menjadi keunggulan Indonesia. Puncak bonus demografi -ketika rasio tanggungan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai titik terendah-diperkirakan berlangsung antara tahun 2020 hingga 2030. Setelah itu, rasio tanggungannya (dependency ratio) akan merangkak naik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 memperlihatkan penduduk usia kerja, baik yang bekerja maupun pengangguran, ada 215,4 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 76,2 persen dari total 282,5 juta penduduk Indonesia. Sementara angka angkatan kerja (penduduk usia produktif yang bekerja atau sedang mencari kerja) mencapai 152,1 juta orang.
Idealnya, bonus demografi ini berpotensi besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena banyaknya tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperlancar jalan menuju pemerataan kesejahteraan.
Namun, bila tidak disertai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pembukaan lebih banyak lapangan kerja, bonus demografi ini bisa menjadi bumerang yang mengancam kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Pengangguran justru berpotensi semakin melimpah.
Saling Salip Indonesia-Vietnam
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan. Terlebih kualitas SDM Indonesia secara umum masih relatif rendah, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Tolok ukurnya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/IPM) yang disusun oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP). IPM mengukur capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat; akses kepada pengetahuan; dan, standar kehidupan yang layak.
Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui harapan hidup saat lahir; dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.
Hasil perhitungan termutakhir yang dirilis oleh UNDP pada tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai IPM Indonesia terbilang rendah bila dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Indonesia dengan nilai IPM 0,71, hanya menempati posisi keenam di Asia Tenggara, di bawah Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Singapura konsisten mencatatkan IPM tertinggi di kawasan ini, jauh meninggalkan yang lain. Sementara di dunia, posisi Indonesia ada di peringkat ke-113.
Memang, angka IPM Indonesia terus naik dari tahun ke tahun, tetapi hal yang sama juga dialami oleh negara lain. Salah satunya adalah Vietnam, negara komunis yang ekonomi dan industrinya berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan negara ini menjadi salah satu pesaing terberat Indonesia, terutama dalam menarik perhatian pemodal asing di kawasan Asia Tenggara.
Hingga awal 1990-an, negara yang belum lama sembuh dari perang saudara itu masih memiliki nilai IPM di bawah Indonesia. Akan tetapi, dipicu oleh Reformasi Doi Moi pada 1986 –kebijakan yang mengubah sistem ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar yang berorientasi pada sosialis– perekonomian dan IPM Vietnam naik secara konsisten.
Indonesia juga perlu waspada karena Filipina kini semakin mendekat. Jika tidak ingin kalah saing dengan negara-negara lain, baik di Asia Tenggara maupun dunia, kualitas SDM di Nusantara harus segera diperbaiki dan ditingkatkan.
Hanya Unggul dari Laos, Kamboja, dan Timur Leste
Kualitas SDM adalah salah satu pertimbangan utama para investor yang ingin masuk menanamkan modal. Ketersediaan tenaga kerja terdidik yang memadai akan menjadi penopang kegiatan usaha yang dijalankan, mengingat SDM -dalam istilah ekonomi- merupakan input penting dalam proses produksi.
Indikator penting untuk melihat kualitas SDM adalah melalui tingkat pendidikan. Dengan begitu, tak ada jalan lain untuk memperbaiki kualitas SDM, kecuali meningkatkan kualitas seluruh jenjang pendidikan.
Untuk indikator pendidikan, posisi Indonesia di Asia Tenggara masih jauh dari baik. Porsi penduduk berusia lebih dari 25 tahun yang berpendidikan strata satu (S1) atau setara, menurut data Bank Dunia (World Bank), hanya unggul dari Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Bahkan dengan Vietnam pun tertinggal jauh.
Pada 2022, rasio penduduk Indonesia yang berusia di atas 25 tahun dan berpendidikan minimal S1 atau setara hanya 9,5 persen dari total penduduk usia 25 tahun ke atas. Bahkan pada 2023, komposisinya turun menjadi 9,33 persen. Sementara Vietnam sudah 11,5 persen.
Naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jumlah lulusannya semakin memprihatinkan. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022, hanya 882.113 orang yang memiliki ijazah S2 (magister), atau 0,45 persen dari angkatan kerja. Sementara lulusan S3 (doktoral) tercatat 63.315 orang atau hanya 0,03 persen dari angkatan kerja. Jumlah yang masih amat minim untuk bisa membawa Indonesia berkompetisi di kancah global dalam beragam hal.
Presiden Joko Widodo saat masih menjabat pernah mengeluhkan kondisi tersebut. Ia menyatakan rasio lulusan S2 dan S3 dengan jumlah penduduk produktif di Malaysia dan Vietnam sudah mencapai 2,43 persen, lima kali lipat dibandingkan Indonesia.
Angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas di Indonesia saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), didominasi oleh lulusan sekolah menengah –SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat. Jumlah mereka mencapai 79,5 juta orang, atau 52,3 persen dari total 152,1 juta angkatan kerja di Indonesia.
Lulusan sekolah dasar (SD) ada di peringkat kedua dengan 34,8 persen atau 53 juta jiwa. Sementara itu, angkatan kerja yang menyandang gelar sarjana baru mencapai 19,6 juta jiwa atau hanya 12,9 persen.
Provinsi dengan alumni pendidikan tinggi terbanyak adalah Jawa Barat, jumlahnya 2,9 juta orang. Namun rasionya hanya 11,3 persen dari 26,2 juta angkatan kerja di provinsi terpadat penduduk itu.
Rasio angkatan kerja berpendidikan tinggi terbaik ada di DKI Jakarta. Itu pun hanya 21 persen dari total 5,4 juta angkatan kerja di sana.
Minimnya angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi tersebut membuat kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan bisa dibilang masih diragukan sehingga akan sulit bersaing dengan tenaga ahli dari negara-negara maju di dunia, bahkan di Asia Tenggara.
Walau demikian, dominannya angkatan kerja lulusan sekolah menengah menunjukkan bahwa ada perkembangan positif dalam dunia pendidikan Indonesia. Program Wajib Belajar 12 tahun tampak berjalan dengan relatif baik.
Menilik Efek Wajib Belajar 12 Tahun
Wajib Belajar (Wajar) dimulai sejak era Presiden Suharto, tepatnya pada 1984. Program tersebut awalnya hanya mewajibkan warga negara usia sekolah untuk belajar hingga tamat SD (6 tahun). Sepuluh tahun kemudian, pada 1994, kewajiban belajar naik menjadi 9 tahun atau hingga tamat SMP.
Lantas, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan warga negara untuk menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat. Kewajiban Menilik Efek Wajib Belajar 12 Tahun tersebut baru mulai dirintis pada 2012 dan diimplementasikan penuh mulai tahun 2015.
Sejak saat itu, gairah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA setelah lulus SMP terus membaik. Nyaris tak ada lagi yang putus sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sejak tahun ajaran 2016/2017, seluruh lulusan SMP melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA. Jumlahnya yang lebih dari 100 persen, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan tambahan dari jenjang pendidikan Tsanawiyah.
Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Ada beberapa indikator yang dapat ditengok, yakni: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).
APS adalah perbandingan jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah dengan yang tidak. Pada tahun 2024, dari total penduduk yang usianya masuk dalam usia bersekolah, hanya 84 dari 100 orang yang menikmati bangku sekolah.
Sementara APK merupakan indikator untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk usia sekolah. Pada 2024, dari penduduk usia sekolah, ada sekitar 74 dari 100 orang yang duduk di bangku SMA sederajat.
Sedangkan APM sebagai indikator untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Ini merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk berusia yang sesuai (dengan jenjang pendidikan tertentu).
Pada 2024 misalnya, persentase APM untuk jenjang pendidikan SMK/SMK sekitar 64,1 persen. Ini menandakan dari sekitar 100 penduduk yang usianya dalam kelompok jenjang pendidikan SMA/SMK, hanya sekitar 64 orang yang bersekolah.
Meski demikian, program wajib belajar 12 tahun ini memang belum berjalan sempurna. Diagram di bawah yang disusun berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa lebih jelas memaparkan arus peserta didik dari SD hingga SMA.
Arus Peserta Didik Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah Tahun 2023/2024

Gambar di atas menunjukkan belum 100 persen siswa lulusan SD yang lanjut ke SMP. Dari 4 juta lulusan SD pada tahun ajaran 2023/2024 hanya 3,4 juta atau 84,3 persen yang lanjut ke SMP, dengan angka putus sekolah mencapai 0,19 persen.
Perlu diperhatikan bahwa data sekolah yang digunakan dalam white paper ini adalah data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sekolah di bawah Kementerian Agama tidak termasuk dalam diagram. Oleh karena itu, ada kemungkinan mereka yang tidak lanjut ke SMP lebih memilih untuk lanjut ke Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau dari SMP pindah ke Madrasah Aliyah (MA) yang setara SMA.
Bisa juga hal sebaliknya yang terjadi, misalnya siswa MTs melanjutkan pendidikan mereka ke SMA atau SMK. Hal tersebut bisa menjelaskan mengapa total jumlah siswa SMA dan SMK tahun ajaran 2023/2024 lebih banyak bila dibandingkan dengan siswa lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan mereka.
Makin Berkurang di Perguruan Tinggi
Pendidikan tinggi, mulai dari Diploma 1 (D1) hingga Strata 1 (S1) adalah jenjang pendidikan berikutnya. Jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan ini pun semakin berkurang.
Mengutip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) total jumlah mahasiswa baru yang masuk ke universitas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,2 juta siswa. Itu pun bukan hanya yang lulus SMA pada 2023, tetapi juga lulusan tahun-tahun sebelumnya.
Sementara, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2023, porsi siswa lulusan SMA dan sederajat yang lanjut ke pendidikan tinggi mencapai 52,6 persen, atau sekitar 1,8 juta orang. Jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan populasi penduduk usia 18-24 tahun yang mencapai 22,6 juta jiwa.
Peningkatan biaya kuliah yang signifikan di tengah kondisi perekonomian yang buruk membuat banyak siswa, juga orang tua mereka, harus berpikir ribuan kali sebelum memutuskan untuk kuliah.
Cara terbaik adalah mencari sumber pendanaan lain, seperti beasiswa dari dalam maupun luar negeri. Namun itu tak mudah didapat karena ketatnya persaingan.
Total jumlah mahasiswa Indonesia berdasarkan data PDDikti mencapai 10,01 juta. Mereka berkuliah di 6.484 kampus, terdiri dari 127 perguruan tinggi negeri (PTN), 4.477 perguruan tinggi swasta (PTS), 1.535 perguruan tinggi akademik (PTA), 241 perguruan tinggi kedinasan (PTK), dan lainnya 104 kampus.
Demi SDM Unggul
Memang gelar pendidikan tinggi tidak lantas membuat seseorang menjadi lebih siap memasuki dunia kerja. Lulusan sekolah vokasi seperti SMK bisa saja lebih piawai mempraktikkan ilmu mereka di lapangan.
Akan tetapi hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi adalah hak asasi manusia. Penyediaan layanan pendidikan yang bermutu secara merata mesti dipandang sebagai bentuk investasi SDM unggul untuk kemajuan pembangunan Indonesia.
Pendidikan juga adalah sarana terbaik bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan memperoleh keadilan.
Tanpa perhatian khusus terhadap dunia pendidikan dan kemudahan akses terhadapnya bagi masyarakat Indonesia, target Indonesia Emas 2045 sepertinya akan jadi impian belaka. Bisa jadi situasinya justru terbalik, yakni menjadi puncak pengangguran.