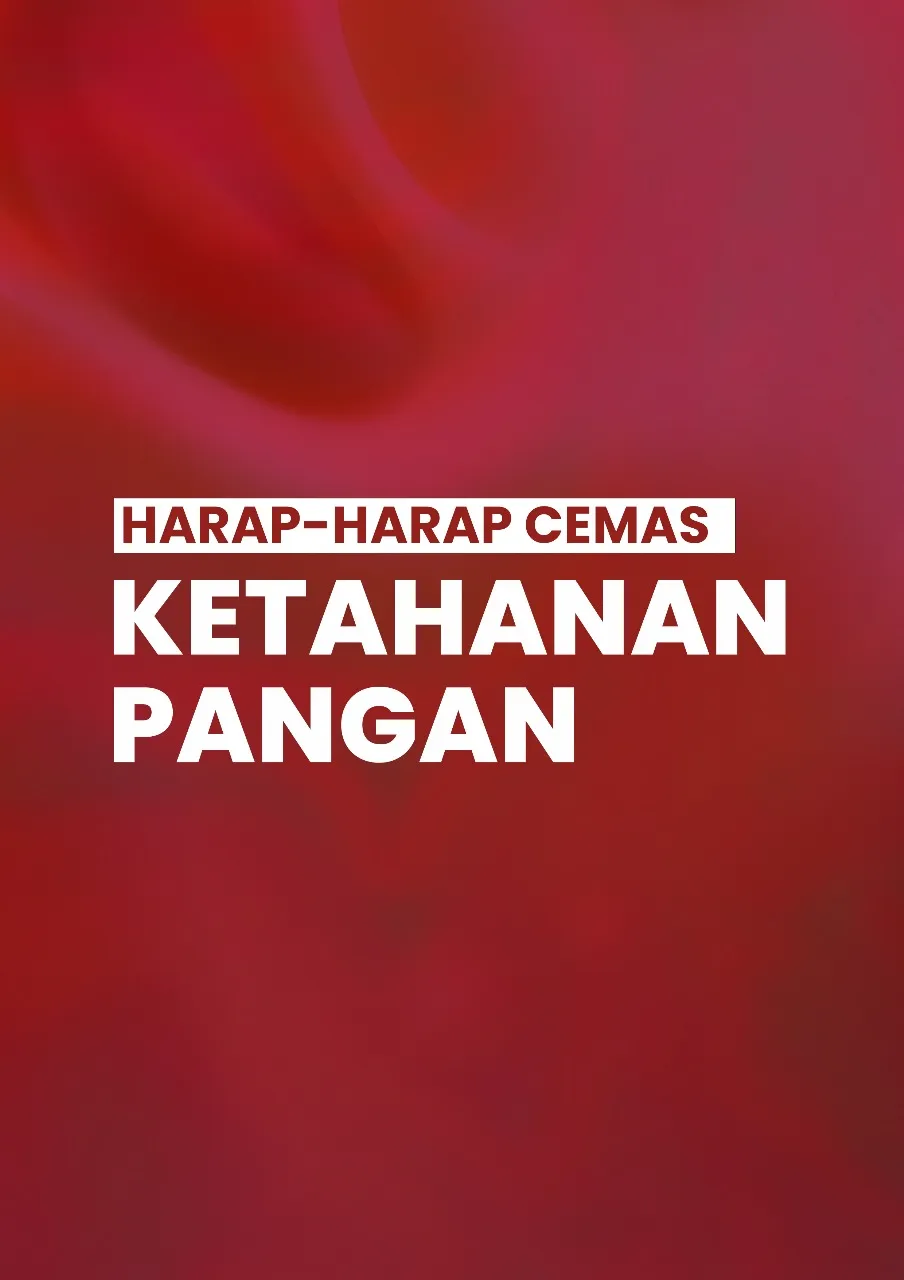Harap-harap Cemas Ketahanan Pangan
28 Mei, 2025
Indonesia memiliki peluang besar mewujudkan ketahanan pangan, jika melihat dari sumber daya yang ada. Komoditas beras dan gula jadi ujian awal.

Keterangan foto: Ilustrasi beras di kaca pembesar.
Ringkasan
• Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional Pemerintahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah masalah kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Pemerintah menargetkan swasembada beras tercapai pada akhir 2025 dan swasembada pangan total pada 2027. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama menuju negara maju dan kemandirian ekonomi nasional.
• Posisi Indonesia dalam Indeks Ketahanan Pangan Masih Moderat
Menurut Global Food Security Index (GFSI) 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dunia dan keempat di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Tantangan utama berada pada pilar ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan pangan, terutama karena lemahnya infrastruktur pertanian dan riset, meski keterjangkauan harga masih relatif baik.
• Tantangan: Impor, Stunting, dan Akses Air Bersih
Kemandirian pangan masih terhambat oleh ketergantungan impor beras dan gula, serta masalah gizi dan air bersih. Meski angka stunting turun menjadi 19,8% pada 2024, masih ada pekerjaan besar untuk memperluas akses air minum layak dan memperkuat regenerasi petani agar ketahanan pangan nasional benar-benar berkelanjutan.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - "Masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika kita ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu." - Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertanian, saat mengikuti telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi). Isu ketahanan pangan memang menjadi krusial, mengingat jumlah populasi Indonesia yang lebih dari 275 juta jiwa, karakteristik geografis kepulauan, serta tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
Ketahanan pangan juga secara langsung memengaruhi kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kedaulatan negara. Di tengah dinamika global seperti isu perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan rantai pasok, orkestrasi kemandirian pangan ditangani secara komando alias imperatif.
Bahkan sejak baru dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa memperkuat ketahanan pangan adalah prioritas utama pemerintahannya. Dalam beberapa kesempatan, dia kerap menegaskan pentingnya ketahanan pangan dan upaya pemerintahannya untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat.
“Jika ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” katanya.
Tak berhenti di pernyataan, Presiden pun memajukan tenggat swasembada pangan dua tahun lebih cepat. Sedianya, target itu akan dicapai paling lambat 2028 atau 2029. Kini, targetnya menjadi 2027. Tapi untuk swasembada beras ditargetkan tercapai pada akhir 2025 atau paling lambat pada 2026. Setelah itu menyusul komoditas jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi.
Bagi Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan adalah agenda strategis yang tidak bisa ditawar. Sebagai negara agraris dan maritim, negeri ini memang memiliki potensi besar untuk dapat mewujudkan ambisi swasembada pangan.
Masih Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam
Analisis terhadap indeks ketahanan pangan internasional memberikan gambaran objektif mengenai kinerja Indonesia. Tolok ukur ketahanan pangan yang diyakini paling sahih saat ini adalah Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis oleh Economist Impact1, lembaga riset dari The Economist Group.
1. Economist Impact adalah laporan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan tim majalah berita mingguan The Economist tentang beragam isu global, terutama yang terkait dengan ekonomi, bisnis, politik, dan teknologi.
GFSI merupakan tolok ukur komprehensif yang mengevaluasi ketahanan pangan di 113 negara berdasarkan empat pilar, yaitu:
1. Affordability (Keterjangkauan): Mengukur kemampuan konsumen untuk membeli makanan, kerentanan mereka terhadap guncangan harga, serta keberadaan program dan kebijakan untuk mendukung konsumen saat terjadi
guncangan.
2. Availability (Ketersediaan): Mengukur produksi pertanian dan kemampuan di lahan pertanian, risiko gangguan pasokan, kapasitas nasional untuk menyebarluaskan makanan, dan upaya penelitian untuk memperluas hasil pertanian.
3. Quality & Safety (Kualitas dan Keamanan): Mengukur variasi dan kualitas gizi makanan secara rata-rata, serta keamanan makanan.
4. Sustainability & Adaptation (Keberlanjutan dan Adaptasi): Menilai eksposur suatu negara terhadap dampak perubahan iklim; kerentanannya terhadap risiko sumber daya alam; dan bagaimana negara tersebut beradaptasi terhadap risiko tersebut.
Pada GFSI terakhir yang dirilis tahun 20222, Indonesia menempati peringkat ke-63 dengan skor total 60,2, naik lima peringkat dari posisi pada tahun 2021. Sementara bila dibandingkan negara-negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menempati peringkat keempat, di bawah Singapura (73,1), Malaysia (69,69), dan Vietnam (67,9).
2. Economist Impact merilis GFSI secara tahunan sejak 2012, tetapi tidak ada laporan terbaru untuk tahun 2023 dan 2024. Tidak ada pernyataan resmi dari tim Economist Impact, maupun The Economist, soal alasan belum dirilisnya indeks terbaru.
Tabel tersebut memperlihatkan posisi Indonesia di peringkat yang moderat, baik di dunia maupun ASEAN. Karena itu, masih terbuka ruang untuk terus memperbaiki ketahanan pangan.
Puncak ketahanan pangan Indonesia terjadi pada tahun 2018 dengan indeks mencapai 63,6. Setelah itu pencapaian indeks terus menurun, terutama akibat melemahnya pilar ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi. Di mana titik lemah ketahanan pangan Indonesia sebenarnya?
Pilar: Ketersediaan (50,9)
Tim Economist Impact menilai pilar ini sebagai salah satu tantangan terberat bagi Indonesia. Setelah sempat mencapai titik tertinggi 57,2 pada tahun 2020, skor ketersediaan jatuh ke angka 50,9 pada 2022.
Dari tujuh indikator penentu skor ketersediaan, lima mendapat nilai merah, yang berarti berada di bawah rata-rata pencapaian 113 negara di dunia yang dicatat oleh Economist Impact. Hasil analisis lembaga tersebut menilai Indonesia masih lemah dalam hal akses dan input sumber daya bagi petani; riset dan pengembangan pertanian; infrastruktur rantai pasok; kecukupan suplai; serta hambatan politik dan sosial terhadap pangan.
Walau demikian, pemerintah Indonesia dinilai masih memiliki komitmen tinggi terhadap kebijakan yang mendukung keamanan akses terhadap pangan. Nilai tinggi lainnya ada pada indikator infrastruktur pertanian, khususnya ketahanan terhadap volatilitas hasil produksi.
Pilar: Keterjangkauan (81,4)
Indonesia mendapatkan nilai yang relatif tinggi, yakni 81,4, untuk aspek keterjangkauan. Artinya harga pangan di Indonesia relatif terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.
Skor untuk Indonesia dalam pilar keterjangkauan pangan ini naik-turun setiap tahun, tetapi tetap terjaga di atas rata-rata dunia. Dengan demikian, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan melalui kebijakan dan program yang
dijalankan.
Nilai tertinggi pada pilar ini didapat dari dua indikator: harga rata-rata pangan (86,5) dan program jaring pengaman sosial terkait pangan (100).
Pilar: Kualitas dan Keamanan (56,2)
Indonesia hanya mendapat satu nilai biru (di atas rata-rata) dari empat indikator pilar kualitas dan keamanan ini. Hasil positif tersebut didapat oleh indikator keamanan pangan.
Economist Impact melihat Indonesia masih lemah pada indikator keragaman makanan pokok; standar nutrisi, dan ketersediaan mikronutrien (nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan).
Pilar: Keberlanjutan dan Adaptasi (46,3)
Indonesia dinilai memiliki manajemen risiko bencana dan kondisi perairan (laut, sungai, dan danau) yang cukup sehat untuk memenuhi kebutuhan protein penduduknya.
Meski demikian, pemerintah dinilai masih lemah dalam menciptakan sistem dan mengadopsi praktik pengelolaan risiko terhadap air dan tanah. Indikator lain yang menyebabkan rendahnya nilai Indonesia pada pilar ini adalah rata-rata tarif Most-Favored Nation (MFN) bea masuk produk pertanian, sekitar 8,6%, yang lebih tinggi dari rata-rata tarif MFN secara keseluruhan, yaitu 8%.
Data pilar ketahanan pangan GFSI tersebut menunjukkan, meski Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, efisiensi sistem pangan dan aspek kualitas serta keberlanjutan perlu dioptimalkan. Upaya tersebut dilakukan untuk menyamai atau bahkan melampaui negara-negara tetangga dengan peringkat GFSI lebih baik dari Indonesia.
Ketahanan Pangan Versi Indonesia
Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah lama memiliki ukuran ketahanan pangannya sendiri, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Pasal 1 Ayat (1) UU Pangan 18/2012 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai: “Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”
Undang-undang tersebut juga menegaskan dua konsep vital yang menjadi prasyarat ketahanan pangan, yaitu:
• Kedaulatan Pangan: Hak mutlak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, serta hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai potensi lokal. Ini adalah pengakuan kontrol penuh atas sistem pangan nasional.
• Kemandirian Pangan: Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan hingga tingkat perseorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, dan kearifan lokal secara bermartabat. Ini adalah tentang mengurangi ketergantungan impor.
Dengan demikian, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara harus bisa menjamin ketersediaan dan kualitas pangan bagi seluruh individu di Indonesia, serta menjaga keberlanjutannya. Selain itu, UU Pangan 18/2012 menegaskan bahwa pangan adalah hak asasi manusia.
UU Pangan sekaligus mengamanatkan pembentukan lembaga pemerintah bidang pangan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional. Lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Saat ini, lembaga yang mengemban tugas tersebut adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas). Badan ini resmi dibentuk pada 29 Juli 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Kehadirannya melanjutkan tugas dan fungsi yang sebelumnya diemban oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP).
Bapanas, yang saat ini dikepalai oleh Arief Prasetyo Adi, memiliki tugas utama melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Berbagai fungsi dijalankan oleh lembaga ini, mulai dari koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan hingga pengawasan keamanan pangan. Secara umum, Bapanas berperan penting menjalankan orkestrasi pengembangan ketahanan pangan dalam ekosistem layanan pangan.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Bapanas menyusun konsep ketahanan pangan dan energi seperti tampak pada gambar di bawah ini.
Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, Bapanas fokus pada tiga aspek utama, yang digunakan untuk menghitung Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang berguna untuk memetakan dan menganalisis kondisi ketahanan pangan di berbagai wilayah di Indonesia.
1. Ketersediaan: Memastikan pasokan pangan yang cukup dari produksi dalam negeri, termasuk melalui pengelolaan cadangan pangan nasional.
2. Keterjangkauan: Menjamin bahwa masyarakat memiliki akses fisik dan ekonomi yang cukup terhadap pangan, termasuk stabilisasi harga agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
3. Pemanfaatan: Memastikan bahwa pangan yang tersedia dan dapat diakses dapat dimanfaatkan dengan baik oleh individu untuk memenuhi kebutuhan gizi, termasuk pencegahan masalah gizi seperti stunting.
Bapanas mengakui bahwa penyusunan IKP mengadopsi pengukuran GFSI, namun dilakukan penyesuaian metodologi agar selaras dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. Tiga aspek utama IKP ada dalam empat pilar Global Food Security Indonesia (GSFI). Hanya saja, Bapanas tidak menjadikan komponen keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation) sebagai indikator IKP.
NEXT Indonesia Center coba menganalisis kondisi terkini ketahanan pangan Indonesia berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan Indonesia yang dipaparkan oleh Bapanas.
Aspek Ketersediaan: Titik Rawan di Beras dan Gula
Untuk melihat kondisi ketersediaan pangan, NEXT Indonesia Center memilih lima komoditas pangan penting yang berkontribusi besar terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) dan garis kemiskinan. Komoditas tersebut adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, dan gula pasir.
Pada publikasi “Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen Hasil Survei Biaya Hidup 2022”3 dapat diketahui pola konsumsi masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan pada periode survei.
3. Publikasi 5 tahunan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) ini berisi informasi tentang paket komoditas serta nilai konsumsinya di kabupaten/kota selama tahun 2022, yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Angkanya diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2022.
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa lima komoditas tersebut memiliki nilai konsumsi dan kontribusi terhadap garis kemiskinan yang relatif tinggi. Dengan demikian, perubahan pada harga jual komoditas tersebut akan berpengaruh besar terhadap pola konsumsi dan perekonomian secara keseluruhan.
Bila IHK naik, berarti terjadi inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Sementara penurunan IHK bermakna terjadi deflasi yang mengindikasikan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi.
Pada 2024, data BPS menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap lima komoditas pangan yang penting telah berhasil dipenuhi pemerintah. Tidak ada jurang lebar antara konsumsi dalam negeri dengan ketersediaan yang diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan impor. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2022.
Walau demikian, stok beras pada tahun 2022 sempat mengalami perubahan negatif sekitar 469 ribu ton. Pada tahun itu konsumsi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan ketersediaan, sehingga pemerintah harus melepas stok beras ke pasar. Beras dan gula pasir adalah komoditas dengan tingkat kerawanan tinggi karena masih amat tergantung pada impor.
Setelah itu, indikatornya berubah positif. Dengan demikian, kondisi stok relatif aman.
Volume impor beras pada tahun 2024 mencapai 4,52 juta ton, naik 47,6% dari total 3,06 juta ton pada tahun 2023.
Tiga negara utama yang memasok beras ke Indonesia itu adalah Thailand (1,36 juta ton; 30,19%), Vietnam (1,25 juta ton; 27,62%), dan Myanmar (831,38 ribu ton; 18,40%). Sisanya datang dari beberapa negara lain, termasuk Pakistan dan India.
Hitung-hitungan Surplus Beras
Tahun ini pemerintah berupaya menggenjot produksi beras agar ambisi yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada beras pada akhir 2025 bisa terwujud. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, dikutip Kompas (3/2/2025), yakin surplus beras akan terealisasi pada akhir tahun ini jika target produksi tercapai.
Stok beras pada awal tahun 2025, menurut Bapanas, tersimpan 8,14 juta ton, sementara target produksi beras adalah 32,29 juta ton. Konsumsi dalam negeri, menurut Astawa, diperkirakan 30,97 juta ton dan ada rencana impor beras khusus4 sebanyak 514.305 ton. Dengan demikian akan tercapai surplus beras 9,97 juta ton pada akhir 2025.
4. Impor beras khusus adalah impor beras yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu, tidak termasuk beras umum yang dikonsumsi sehari-hari. Contohnya, beras ketan, beras kukus, beras Hom Mali, beras japonica, atau beras basmati.
Produksi padi nasional menunjukkan perkembangan positif pada periode awal 2025. BPS mencatat luas panen padi pada Februari 2025 mencapai 0,76 juta hektare, naik 63,53% dibandingkan Februari 2024 yang hanya sebesar 0,46 juta hektare.
Produksi padi Februari 2025 diperkirakan mencapai 3,88 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 60,86% dibandingkan Februari tahun lalu yang sebesar 2,41 juta ton GKG. BPS juga memperkirakan potensi luas panen pada Maret–Mei 2025 mencapai 4,30 juta hektare, naik 0,23 juta hektare year-on-year.
Mengenai beras impor, BPS mencatat pada Januari-Maret 2025 volumenya sudah mencapai 112 ribu ton. Jumlah itu setara dengan 21,8% dari total rencana impor beras khusus.
Gula: Impor atau Tidak?
Beralih ke gula pasir. Impor komoditas pangan penting ini tampak fluktuatif pada periode 2022-2024. Volumenya terbilang besar, berkisar antara 5-6 juta ton setiap tahun. Sementara produksi dalam negeri rata-rata hanya sedikit di atas 2 juta ton.
Melihat besarnya kebutuhan impor tersebut, ketika Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Desember 2024 menyatakan ingin menyudahi impor gula mulai tahun 2025, tak sedikit orang yang skeptis. Terbukti pada Februari 2025, pemerintah berbalik arah dengan mengumumkan rencana impor 200.000 ton gula mentah untuk menambah cadangan gula pemerintah (CGP) yang menipis.
Pemerintah telah menetapkan target produksi gula konsumsi5 2,59 juta ton hingga akhir 2025. Dengan perkiraan konsumsi mencapai 3,4 juta ton, berarti masih ada kebutuhan impor sebesar 850 ribu ton.
5. Gula konsumsi adalah gula yang dirancang untuk dikonsumsi langsung masyarakat.
Oleh sebab itu, target swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan gula industri6 pada 2030 bisa dibilang sangat ambisius. Perluasan lahan pertanian tebu ke luar Pulau Jawa dan peningkatan produktivitas pada lahan-lahan yang telah ada menjadi cara terbaik untuk dapat mencapai ambisi besar tersebut.
6. Gula industri diproduksi untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan dan minuman.
Sementara itu, komoditas bawang merah, ayam ras, dan telur ayam ras terbilang aman untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Aspek Keterjangkauan: Menyeimbangkan Inflasi dan Daya Beli
Harga pangan sering kali menjadi isu sensitif dan dapat memicu gejolak sosial. Kenaikan harga pangan yang tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan sosial serta politik.
Oleh karena itu, pemerintah merancang dan menjalankan beragam program untuk dapat terus menjaga agar harga pangan tetap terjangkau. Beberapa di antaranya, kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), operasi pasar, pengawasan dan penetapan harga eceran tertinggi (HET), bantuan sosial, serta beragam subsidi.
Program-program tersebut berhasil menjaga keterjangkauan pangan, sehingga Indonesia mendapatkan nilai tinggi pada indikator ini dalam GFSI. Bahkan program jaring pengaman sosial mendapatkan nilai 100.
Waspada Irama Harga Pangan
Salah satu poin penting dalam menjaga kestabilan harga pangan adalah mengendalikan inflasi umum, dan inflasi pangan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sudah sejak tahun 2010-an Bank Indonesia menginisiasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengendalikan inflasi yang disebabkan kenaikan harga pangan.
Sumber inflasi yang paling diwaspadai adalah “volatile food”, yaitu komoditas dalam kategori makanan yang harganya sangat sensitif terhadap faktor-faktor kejutan, sehingga bisa naik atau turun dengan tajam. Faktor- faktor kejutan itu adalah situasi yang bisa mendadak terjadi, seperti masa panen, gangguan alam, serta perkembangan harga domestik dan internasional.
Akibat faktor kejutan itu, irama perubahan harga pangan bisa tak beraturan. Sejumlah komoditas, yakni beras, daging ayam ras, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah termasuk dalam kategori “volatile food”. Gejolak yang terjadi pada harga komoditas-komoditas tersebut serta merta memberikan guncangan pada kantong masyarakat.
Pada grafik di atas tampak pergerakan inflasi makanan lebih tajam dan tak beraturan bila dibandingkan dengan inflasi umum. Volatilitas inflasi makanan berpengaruh besar terhadap naik-turunnya inflasi secara keseluruhan.
Kewaspadaan pemerintah terhadap “volatile food” biasanya meningkat sepanjang periode Idul Fitri. Pada waktu-waktu tersebut, Kementerian Keuangan akan memberi anggaran tambahan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menstabilkan harga bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Perhatikan Upah Pekerja
Hal lain yang penting untuk diperhatikan untuk menjaga aspek keterjangkauan pangan adalah upah pekerja. Sangat penting untuk selalu menyesuaikan upah minimum dengan inflasi, sehingga kebutuhan dasar para pekerja dan keluarga mereka dapat terpenuhi.
Kenaikan harga pangan yang tinggi tanpa dibarengi kesesuaian upah akan menggerus daya beli dan menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Hingga akhir 2024, meski tipis, kenaikan upah minimum tampak lebih besar dari angka inflasi. Dengan demikian, harga pangan masih terjangkau oleh masyarakat, termasuk yang mendapatkan upah minimum.
Kabar baik lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS menunjukkan penurunan jumlah individu dalam rumah tangga yang tidak makan seharian. Jumlah penduduk, baik di kota maupun desa, yang tidak bisa makan seharian pada tahun 2024 tercatat 685.496 orang, turun 9,15% dibandingkan tahun 2020. Persoalan ini pekerjaan rumah penting yang mesti diselesaikan. Pemerintah memiliki kewajiban merawatnya, sesuai amanat konstitusi.
Namun, ada catatan penting dari data Susenas. Dalam lima tahun terakhir, lebih banyak warga kota yang pernah tidak makan seharian bila dibandingkan masyarakat desa. Pada tahun 2024 misalnya, 60,5% dari total warga yang pernah tidak makan seharian (dalam satu tahun) adalah penduduk yang tinggal di kota.
Pemerintah sepertinya perlu menaruh perhatian lebih kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tinggal di perkotaan.
Aspek Pemanfaatan: Kendala Ketersediaan Air Minum Layak
Bila pangan sudah tersedia dan harganya terjangkau, muncul beberapa pertanyaan berikutnya, seperti: Apakah pangan tersebut sudah mencukupi kebutuhan gizi? Bagaimana mutu dan keamanannya? Makanan yang membuat perut kenyang belum tentu membuat tubuh menjadi lebih sehat.
Pentingnya asupan pangan bergizi itu membuat prevalensi stunting menjadi salah satu indikator dalam aspek pemanfaatan pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Bapanas.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (di bawah 5 tahun) akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) – sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya. Stunting memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas anak di kemudian hari.
Hingga saat ini, pemerintah masih berupaya untuk terus menurunkan angka stunting. Tak hanya demi kehidupan anak, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan masa depan bangsa karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Peneliti dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEK) Kementerian Pertanian7 menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pekerja. Kondisi tersebut berpotensi menggerus 11% Produk Domestik Bruto (PDB), serta berpotensi mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%.
7. “The Potential of Economic Loss Due to Stunting in Indonesia” oleh Esty A. Suryana (2023) – Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, Volume 8 Nomor 1, Juni 2023.
Data stunting di Indonesia pertama kali dirilis oleh Bank Dunia dalam “World Development Indicators” tahun 1996. Saat itu, prevalensinya mencapai 48,1% pada penduduk usia di bawah 5 tahun. Pemerintah Indonesia baru merilis data stunting secara resmi sejak tahun 2013, dengan angka prevalensi stunting saat itu sebesar 37,2%.
Pemantauan terakhir Bank Dunia menunjukkan tingkat stunting Indonesia mencapai 22% pada 2023, ketiga terburuk di antara negara-negara ASEAN setelah Laos dan Filipina. Sementara angka stunting dunia mencapai 22,3%, sehingga sekitar satu dari lima anak di dunia cenderung lebih pendek dari seharusnya.
Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Beragam program di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilakukan untuk mewujudkan target menurunkan prevalensi stunting penduduk di bawah usia 5 tahun hingga ke angka 14% pada tahun 2024.
Target tersebut tidak tercapai, karena hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting pada 2024 mencapai 19,8%. Meski gagal mencapai target 14%, prevalensi stunting tersebut lebih rendah dari 21,6% yang tercatat pada SSGI 2022.
Beragam intervensi, seperti pemeriksaan kehamilan, pencegahan anemia pada calon ibu, promosi ASI eksklusif, pemantauan balita, hingga penyediaan air bersih dan sanitasi layak, perlu semakin digalakkan pemerintah untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. Apalagi pemerintah telah memasang target penurunan prevalensi stunting menjadi 18% pada 2025.
Menjaga Akses Air Bersih
Manusia boleh jadi masih bisa bertahan hidup lebih dari satu bulan tanpa makan. Tetapi tanpa air, manusia hanya bisa bertahan hidup kurang dari seminggu. Jadi, akses terhadap air bersih dan layak untuk diminum sangat penting bagi keberlangsungan peradaban.
Di Indonesia, akses rumah tangga terhadap air minum layak8 menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Pada tahun 2010, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan baru 44,19% rumah tangga yang punya akses terhadap air minum layak. Persentasenya melonjak menjadi 92,64% pada tahun 2024. Rumah tangga di perkotaan di semua provinsi memiliki akses air minum layak yang lebih baik dari para penduduk desa.
8. Mengacu pada metadata SDGs, rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan.
Kalau dilihat per provinsi, Papua Pegunungan menjadi wilayah yang paling tertinggal soal akses terhadap air bersih ini. Baru 30,64% rumah tangga yang menyatakan mudah untuk mendapatkannya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menetapkan target 100% rumah tangga bisa mengakses air minum layak pada tahun 2045. Tetapi Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dikutip Tempo.co, menyatakan pemerintah berharap bisa mencapainya pada 2030.
Pekerjaan rumah yang besar adalah memperluas jaringan air minum perpipaan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin kepastian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pengaliran air minum yang aman untuk dikonsumsi.
Saat ini baru 19,79% rumah tangga memiliki akses kepada jaringan air minum perpipaan. Sementara target pemerintah sebelumnya adalah mencapai 30,45% pada 2024.
Wamen Diana menyatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan tersebut agar bisa segera mencapai target. Dia juga menyatakan telah mendorong 59 pemerintah daerah untuk turut mewujudkannya, dengan memberikan dukungan finansial kepada BUMD air minum.
“Semua tugas itu kalau dilakukan sendiri-sendiri, kita tidak akan tercapai-capai. Ini harus masif, harus bersama-sama, kita harus saling terintegrasi. Ini tugas kita,” kata Wamen Diana.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
Meskipun ambisius, implementasi semua rencana untuk memperkuat ketahanan pangan ini akan menghadapi berbagai tantangan, antara lain: konversi lahan pertanian, dampak perubahan iklim (kekeringan/banjir), ketersediaan air yang memadai, regenerasi petani, serta efisiensi infrastruktur dan logistik.
Namun, dengan dukungan politik yang kuat, kolaborasi lintas sektor, investasi teknologi yang signifikan, dan partisipasi aktif masyarakat, target swasembada pangan yang diusung oleh Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki prospek tinggi untuk direalisasikan. Bila terwujud, pencapaian tersebut tak hanya akan memperkuat ketahanan pangan domestik, tetapi juga bisa memosisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam keamanan pangan regional dan global.
Karena itu, rasanya tidak berlebihan jika pemerintah menjamin ketersediaan lahan pertanian melalui regulasi. Misalnya, larangan mengonversi lahan pertanian untuk sektor usaha lain.
Namun, kebijakan itu baru mampu memenuhi segelintir dari aspek ketahanan pangan. Masih ada pekerjaan rumah lainnya yang perlu dukungan komitmen secara politik di tingkat pusat.