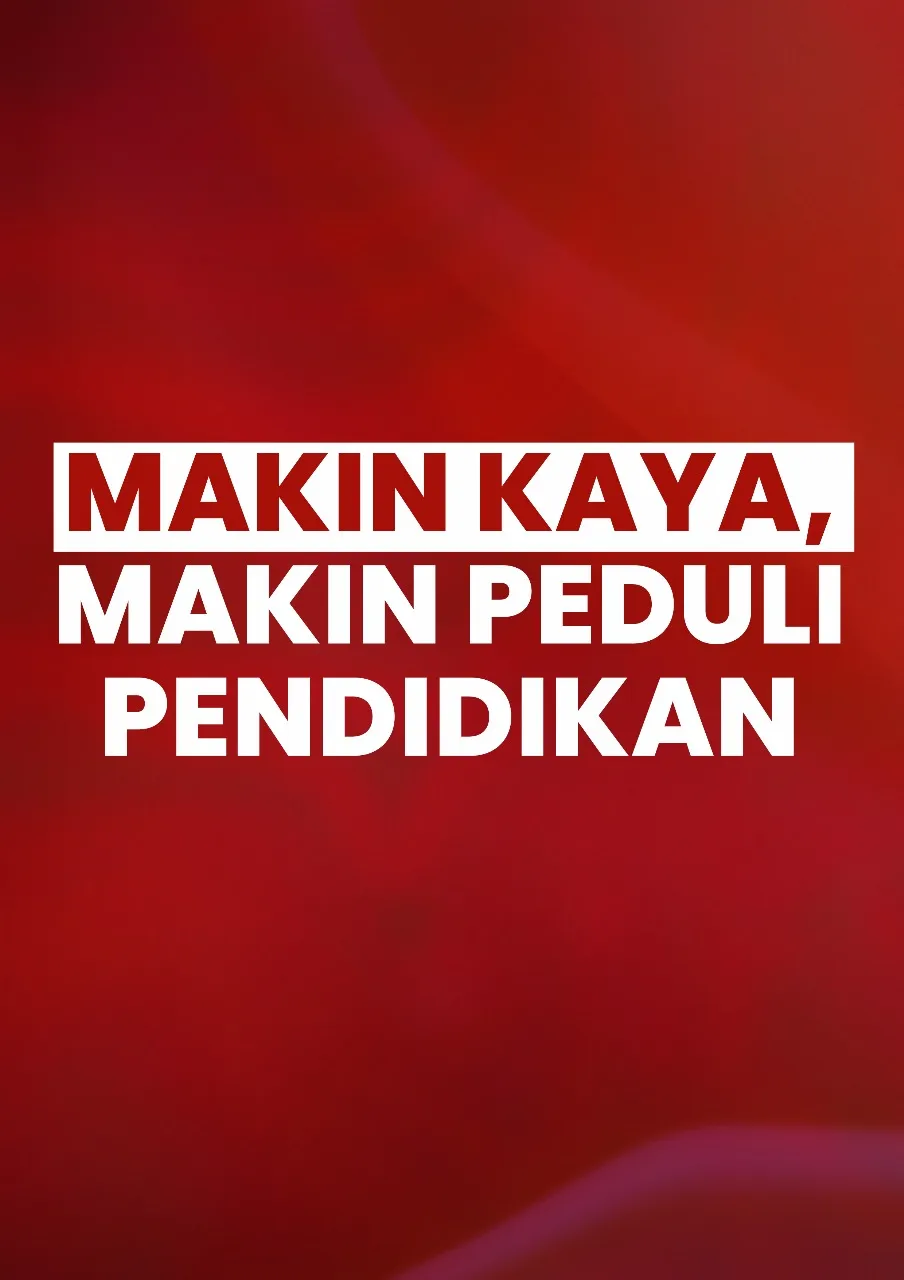Makin Kaya, Makin Peduli Pendidikan
25 Juni, 2025
Ketika biaya pendidikan di Indonesia terus naik, di Vietnam justru turun. Keluarga berkantong tebal semakin rela keluarkan dana lebih untuk pendidikan

Keterangan foto: Ilustrasi topi toga.
Ringkasan
• Biaya Pendidikan Naik Lebih Cepat dari Inflasi Umum
Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia melampaui inflasi umum dan menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan anak usia dini.
• Kualitas dan Akses Pendidikan Tertinggal dari Negara Tetangga
Vietnam berhasil menekan biaya pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya, terbukti dari skor PISA dan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
• Ketimpangan dan Kesejahteraan Pendidik Masih Jadi Masalah
Keluarga kaya lebih banyak mengalokasikan dana untuk pendidikan, sementara kesejahteraan pekerja sektor pendidikan stagnan dan di bawah rata-rata, menghambat peningkatan kualitas pendidikan nasional.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tapi peningkatan biaya yang harus dibayar peserta didik, justru berada di atas rata-rata kenaikan harga atau inflasi umum.
Padahal, di lain sisi, warga negara Indonesia berhak mengenyam pendidikan, karena telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi tersebut mengamanatkan negara harus bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di seluruh Tanah Air. Ayat 2 pasal 31 UUD 1945 bahkan menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, sejak era Orde Baru, pemerintah telah merancang dan melaksanakan program “wajib belajar” yang terus dikembangkan hingga sekarang. Program ini dimulai dengan diluncurkannya wajib belajar 6 tahun (SD/sederajat) oleh Presiden Suharto pada 2 Mei 1984 dan dipayungi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pemerintah memulai wajib belajar 9 tahun seiring dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dasar hukumnya lantas diperkuat melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, “Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”
Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, muncul wacana penambahan rentang waktu wajib belajar menjadi 12 tahun. Sebagai landasan hukum, keluar Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Pada ayat 2 pasal 3 PP tersebut termaktub “Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.”
Keharusan belajar 12 tahun belum secara resmi ditetapkan sebagai program wajib nasional melalui sebuah UU. Aturannya masih berupa PP, yang kekuatannya di bawah UU. Kini, pemerintah tengah menggodok rencana wacana wajib belajar 13 tahun, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Program wajib belajar ini penting untuk dijaga dan dilanjutkan, karena selain menjamin pemenuhan hak warga negara, juga untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Apalagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mencanangkan cita- cita besar “Indonesia Emas 2045”. Peta jalan telah disusun dan resmi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Visi besar RPJPN adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan ketika mencapai usia 100 tahun. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi satu di antara faktor utama pendukung terwujudnya cita-cita tersebut.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa kenaikan biaya yang terus-menerus, sebuah fenomena yang dikenal sebagai inflasi pendidikan. Kenaikan biaya ini berpotensi menghambat aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi sebagian besar masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.
Permasalahan ini bukan sekadar fluktuasi harga biasa. Dinamika ekonomi sektor pendidikan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan pembangunan yang mendalam. Dalam publikasi ini, NEXT Indonesia Center menguraikan kontribusi inflasi pendidikan terhadap inflasi umum, perbandingan pendidikan di Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN, peran pengeluaran pendidikan dalam rumah tangga, serta perkembangan kesejahteraan para pekerja di sektor pendidikan. Data utama dalam laporan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, serta dilengkapi dengan analisis kualitatif dari berbagai sumber yang relevan.
Inflasi Pendidikan Vs Inflasi Umum
Inflasi pendidikan dapat memengaruhi aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat. Kenaikan biaya yang tidak diiringi penambahan pendapatan, berpotensi meningkatkan beban rumah tangga dan menghambat partisipasi pendidikan.
Pada Mei 2025 misalnya, inflasi sektor pendidikan1 mencapai 1,88% Inflasi Pendidikan Vs Inflasi Umum dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year, yoy), tidak beranjak dari angka yang sama sejak Februari 2025. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi umum pada bulan yang sama, yakni mencapai 1,60% yoy. Sektor pendidikan memberikan sumbangan terhadap inflasi tahunan secara keseluruhan sebesar 0,11%.
1. Peningkatan biaya pendidikan dari waktu ke waktu, termasuk biaya sekolah, buku, seragam, transportasi, hingga biaya tambahan lainnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam enam tahun terakhir, inflasi sektor pendidikan beberapa kali naik lebih tinggi dari inflasi umum. Bahkan secara keseluruhan, kenaikan biaya pendidikan lebih konsisten ketimbang biaya lain.
Stabilnya tren peningkatan inflasi sektor pendidikan ketika inflasi umum tampak fluktuatif mengindikasikan bahwa biaya pendidikan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan internal dalam sektor itu sendiri. Bukan semata-mata terseret siklus2 ekonomi.
2. Pola naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, yang ditandai dengan fase ekspansi (pertumbuhan) dan kontraksi (resesi).
Faktor struktural dan internal tersebut semisal kenaikan beragam biaya yang harus ditanggung oleh para wali murid. Meskipun biaya pendidikan SD dan SMP negeri “gratis” secara regulasi, tetapi wali murid kerap dihadapkan pada berbagai biaya tersembunyi seperti seragam, buku, maupun iuran komite.
Biaya-biaya ini, walau terbilang kecil secara individual, dapat menjadi beban yang signifikan bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah memang menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)3 untuk menutupi sebagian biaya ini, namun efisiensi dan alokasi dana tersebut masih kerap menjadi pertanyaan.
3. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk membantu biaya operasional sekolah, baik negeri maupun swasta, dalam menyelenggarakan pendidikan.
Tekanan inflasi tertinggi justru dirasakan pada tingkat pendidikan paling rendah. Inflasi pada subsektor pendidikan dasar dan anak usia dini mencapai 2,74% yoy. Kenaikan ini mencerminkan tekanan ekonomi dari sektor pendidikan telah dirasakan keluarga sejak awal jenjang pendidikan anak.
Para orang tua baru atau calon orang tua mesti bersiap lebih awal untuk mengantisipasi terus naiknya biaya pendidikan dasar dan usia dini ini. Sebagai contoh, dengan cara membuka tabungan dan/atau asuransi pendidikan.
Inflasi terendah justru terjadi pada subsektor pendidikan tinggi yang hanya 1,39%, walaupun tetap menunjukkan adanya kenaikan biaya kuliah secara konsisten. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan saat pandemi Covid-19 membuat kenaikan harga pendidikan menjadi tantangan tersendiri.
Ketika pendapatan masyarakat tidak tumbuh sebanding dengan kenaikan biaya pendidikan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas bisa menjadi tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah dalam mengendalikan biaya pendidikan agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Jangan Risi Mengintip Vietnam
Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN (Asosiasi Negara- Negara Asia Tenggara), inflasi pendidikan Indonesia sebenarnya berada pada tingkat yang moderat. Peringkatnya menempati kelima terendah, di bawah Vietnam, Brunei, Singapura, dan Thailand.
Data di atas menunjukkan bahwa Vietnam berhasil menekan laju inflasi tahunan untuk sektor pendidikannya. Pada Desember 2024 dan Maret 2025 justru terjadi deflasi, yang mengindikasikan terjadinya penurunan biaya pendidikan.
Penurunan biaya pendidikan tersebut bisa menjadi indikator bahwa pemerintah Vietnam tengah berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah. Media lokal VietNam News mengabarkan, beberapa Perbandingan Inflasi Pendidikan Negara ASEAN provinsi dan kota menurunkan atau menghapuskan biaya pendidikan, terutama biaya sekolah negeri untuk tahun ajaran 2024/2025.
Tak sekadar berupaya meningkatkan akses pendidikan, pemerintah Vietnam juga terus berikhtiar meningkatkan kualitas pendidikannya. Majalah The Economist menuliskan bahwa meski Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Vietnam termasuk rendah di Asia Tenggara–US$4.700 per kapita pada 2024–tetapi kualitas pendidikannya terbilang mengagumkan.
Pada tahun 2022, skor Programme for International Student Assessment (PISA) pelajar Vietnam mencapai nilai rata-rata 468, hanya kalah dari Singapura (560) di Asia Tenggara. PISA adalah studi yang digelar oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) setiap tiga tahun untuk mengukur dan membandingkan kinerja siswa berusia 15 tahun di berbagai negara dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Nilai PISA dapat menjadi cermin kualitas sektor pendidikan suatu negara, serta daya saing pelajar-pelajar mereka di kancah internasional.
Pada saat yang sama, nilai rata-rata PISA pelajar Indonesia adalah 369, hanya menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Selain Singapura dan Vietnam, nilai PISA Indonesia lebih rendah dari Brunei (439), Malaysia (404), dan Thailand (394).
Tolok ukur lain yang bisa dilihat untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). IPM yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menjadi alat ukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara. IPM mengukur tiga dimensi utama: umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak.
Grafik perkembangan IPM di atas menunjukkan bahwa Vietnam berhasil mencapai pembangunan manusia yang lebih baik dari Indonesia sejak tahun 1999 dan belum tersusul lagi hingga saat ini. Bahkan selisih keunggulannya semakin tinggi.
Jika indikator pendidikan dilihat dalam komponen IPM, tampak jelas, sejak tahun 2004 Vietnam telah berlari meninggalkan Indonesia. Bahkan mulai tahun 2020, Vietnam unggul di seluruh komponen pendidikan pembentuk IPM.
Jurang terbesar terlihat pada ekspektasi lama sekolah yang berbeda hampir dua tahun. Data World Development Indicators tahun 2023 yang dirilis Bank Dunia menunjukkan bahwa porsi penduduk berusia 25 tahun ke atas yang bergelar sarjana di Vietnam lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia hanya menempati peringkat ketujuh. Kecilnya porsi penduduk berpendidikan tinggi tersebut membuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan masih meragukan. Tak heran jika masih sulit bersaing dengan tenaga ahli dari negara-negara maju di dunia, bahkan di Asia Tenggara.
Secara tradisi, warga Vietnam amat mengagungkan pendidikan. Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan akses bagi masyarakatnya di setiap jenjang pendidikan. Sementara warga, termasuk yang berpenghasilan rendah, rela bekerja lebih keras untuk memberi pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.
Hasilnya sudah terlihat. Kualitas sumber daya manusia adalah salah satu faktor penentu dalam meningkatkan daya saing sebuah negara di pasar global. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja muda dengan skill yang semakin mumpuni–kunci dalam industri padat karya–membuat Vietnam semakin menarik perhatian para investor. Vietnam sudah memetik hasilnya: pertumbuhan ekonomi negara tersebut dalam 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 6,11%, lebih tinggi dari Indonesia yang rata-rata sekitar 5%.
Kesenjangan pengembangan pendidikan antara Indonesia dengan Vietnam merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dikejar. Terutama dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Jika para pemangku kepentingan pada sektor pendidikan tidak segera melakukan perbaikan, Indonesia bakal semakin tertinggal, bukan hanya dari Vietnam tetapi juga dari negara Asia Tenggara lainnya, apalagi dunia.
Sepertinya sudah saatnya Indonesia belajar dari Vietnam soal cara meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan risi.
Kelas Atas Lebih Peduli Pendidikan
Kelas atas dari sisi ekonomi di Indonesia terbukti lebih peduli pendidikan. Isyarat tersebut ditunjukkan melalui porsi konsumsi atau biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan jauh melampaui pengeluaran masyarakat berkantong pas-pasan.
Konsumsi pendidikan merupakan satu di antara komponen yang menyusun Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu harga yang dibayar konsumen untuk 11 kelompok barang dan jasa yang umum dikonsumsi. Indeks ini digunakan untuk menghitung inflasi, yaitu tingkat perubahan harga secara umum dari waktu ke waktu.
Dasar perhitungan IHK didapat dari hasil Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). SBH digelar lima tahun sekali untuk mengumpulkan data tentang pola konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan paket komoditas dan bobotnya dalam perhitungan IHK. Survei terbaru dilakukan pada tahun 2022 yang hasilnya diuraikan dalam tabel di bawah.
Hasil survei BPS itu menemukan bahwa masyarakat Indonesia merogoh kocek hingga Rp138,0 triliun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Porsinya 5,73% dari total nilai konsumsi masyarakat yang tercatat Rp2,4 kuadriliun.
Nilai konsumsi kelompok pendidikan memang bukan yang terbesar. Namun, komponen pendidikan tetap ikut berperan penting dalam menentukan laju inflasi.
Konsumsi pendidikan mencakup berbagai aspek pengeluaran yang terkait, seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Uang Kuliah Tunggal (UKT), pembelian buku, peralatan sekolah, hingga biaya les atau kursus.
Dari tabel di atas, tampak bahwa pengeluaran untuk pendidikan tinggi merupakan komponen yang paling besar, yakni mencapai Rp52,2 triliun. Konsumsi pendidikan dasar menyusul di posisi kedua dengan nilai konsumsi Rp22,3 triliun.
Siapa yang mengeluarkan uang paling banyak untuk biaya pendidikan? Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, yang juga dilakukan oleh BPS, bisa digunakan untuk mengetahuinya.
Kelompok keluarga kelas atas (pengeluaran di atas Rp6 juta/orang/bulan) dan kelas menengah (pengeluaran antara Rp1,2 juta-6 juta/orang/bulan) memiliki porsi anggaran pendidikan tertinggi. Sebesar 20,26% dari total pengeluaran bulanan kelompok kelas atas dihabiskan untuk membiayai pendidikan. Kelas menengah mengalokasikan sekitar 12,27%.
Sementara pada tiga kelas paling bawah, miskin (pengeluaran di bawah Rp354.000/orang/bulan), rentan miskin (pengeluaran Rp354.000-532.000/orang/bulan), dan menuju kelas menengah (pengeluaran Rp532.000-1,2 juta/orang/bulan) porsi pengeluaran untuk biaya pendidikan terbilang kecil. Kisaran alokasinya adalah 5,34-6,33% terhadap total pengeluarannya.
Data tersebut bisa dibaca bahwa mereka yang berpenghasilan besar rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Sementara mereka yang berpenghasilan kecil sulit mengalokasikan dana lebih besar untuk pendidikan, yang boleh jadi karena ada kebutuhan hidup lain yang dianggap lebih penting.
Akan menjadi berbahaya bagi masa depan bangsa kalau ternyata warga berpenghasilan kecil menganggap bahwa pengeluaran pendidikan tidak penting. Kelompok miskin, rentan miskin, dan menuju kelas menengah adalah mayoritas di Indonesia, mencapai 79% dari total jumlah rumah tangga.
Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk membuka akses seluas-luasnya kepada pendidikan yang berkualitas dan murah, atau bahkan gratis, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai bonus demografi4 yang kerap didengung-dengungkan malah akan menjadi beban jika mayoritas adalah warga berpendidikan rendah.
4. Kondisi di mana suatu negara memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Kondisi ini dianggap sebagai peluang emas bagi negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena adanya potensi peningkatan produktivitas dan tenaga kerja.
Kesejahteraan Pendidik Terabaikan
Tak kalah penting untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan adalah orang-orang yang bekerja di sektor jasa pendidikan. Kesejahteraan mereka, mulai dari staf pengajar, tenaga administrasi, hingga penjaga sekolah, harus terus diperhatikan dan diperbaiki.
Perkembangan upah sektor jasa pendidikan terbilang stagnan dalam satu dekade terakhir. Bahkan sejak tahun 2019, besarannya selalu di bawah rata-rata upah sektoral.
Sulit untuk mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan bila para pekerja yang berkutat dan bertanggung jawab pada bidang tersebut belum mendapatkan penghargaan layak. Jangan sampai para guru terus dijuluki “pahlawan tanpa tanda jasa”. Penghargaan berupa upah yang layak akan membuat mereka lebih bersemangat dan fokus dalam menjalankan tugas.
Cara Vietnam untuk menghargai pengajar, sekaligus memperluas jangkauan pendidikan, mungkin bisa ditiru. Negara tersebut memberikan upah lebih besar kepada para guru yang ditempatkan di daerah terpencil. Selain itu, para guru di Vietnam juga mendapatkan berbagai tunjangan sehingga mereka, seperti ditulis Vietnam News, “dapat mengajar tanpa perlu khawatir gajinya tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”
Akhirnya, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perlu mendapat perhatian lebih serius dari para pemangku kepentingan, jika Indonesia tak ingin tertinggal lebih jauh dari negara-negara lain. Pendidikan yang lebih baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia hingga daerah terpencil adalah kunci utama untuk bisa menjadi sebuah “Negara Besar” seperti yang kerap diutarakan Presiden Prabowo Subianto.