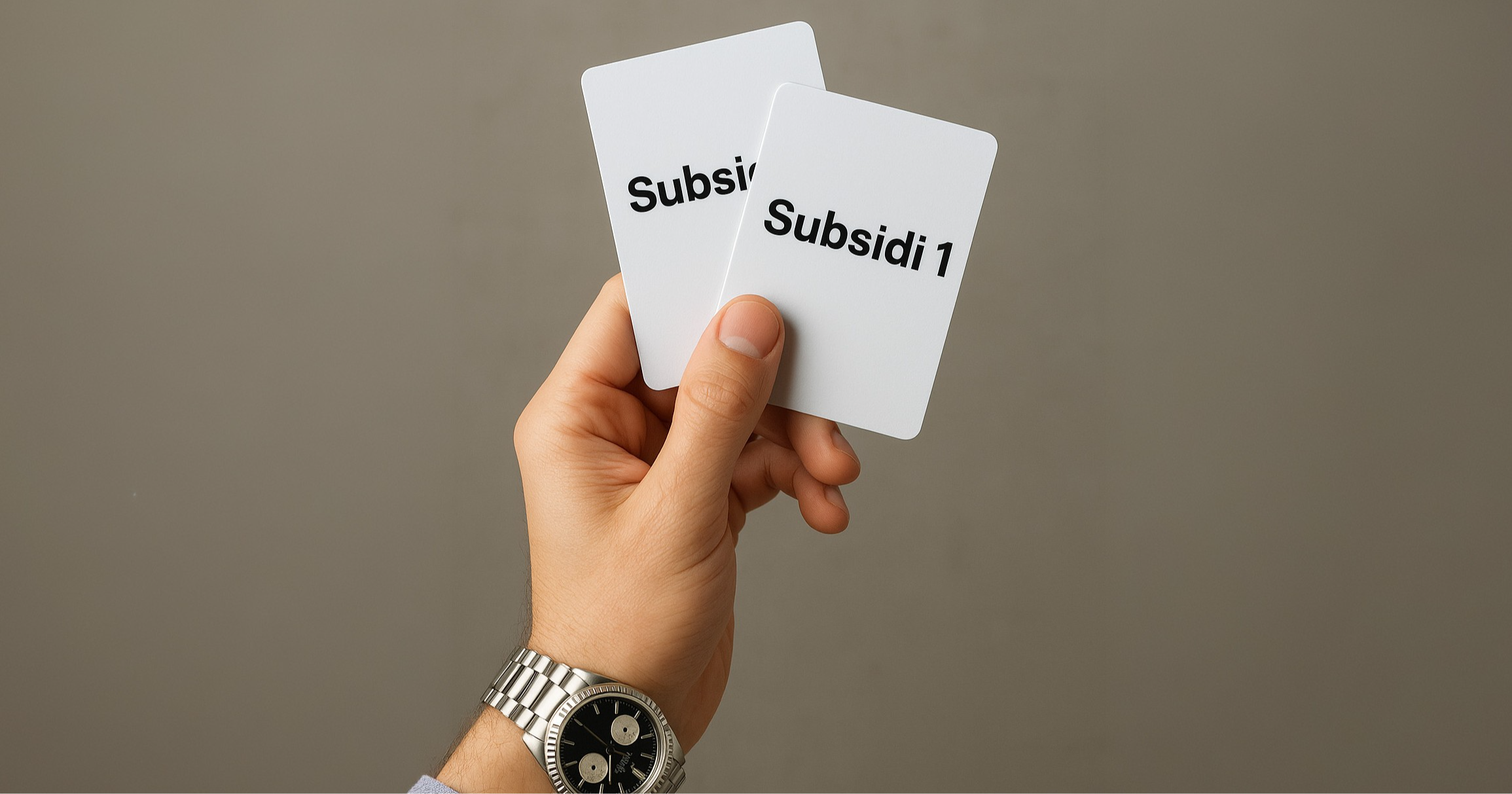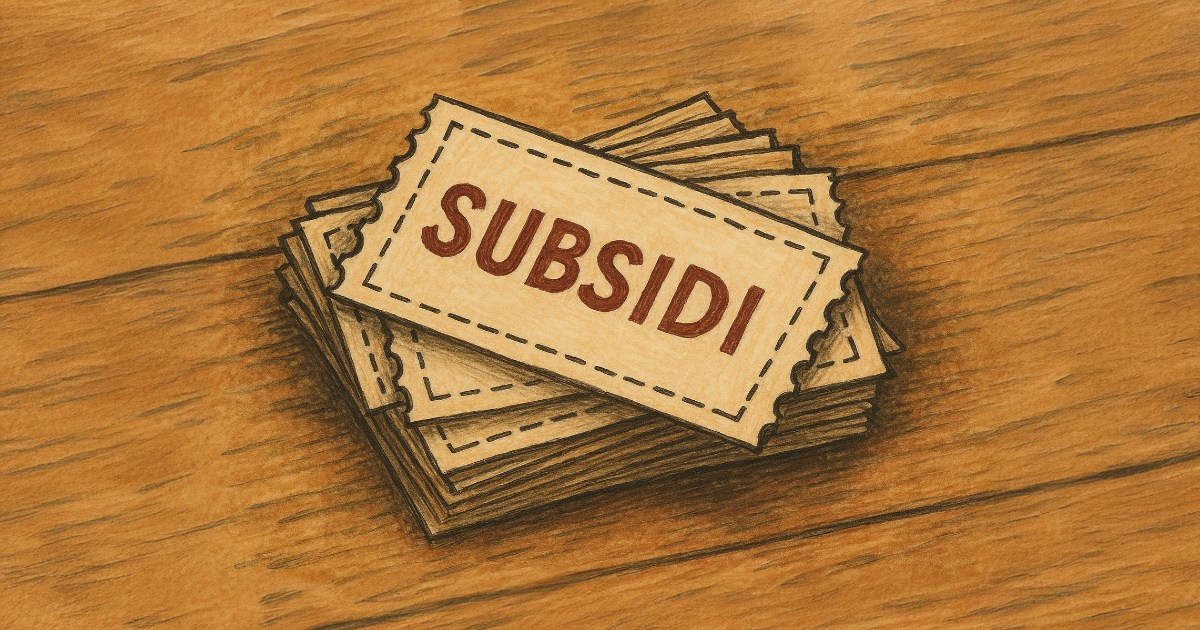Sinyal Positif Industrialisasi
21 November, 2025
Industri pengolahan tumbuh dua triwulan beruntun pada 2025. Jika momentum terjaga, kebangkitan industrialisasi bisa terjadi.

Keterangan foto: Ilustrasi pabrik.
Ringkasan
• Pertumbuhan Melebihi Ekonomi Nasional
Industri pengolahan tumbuh lebih cepat dari ekonomi nasional selama dua triwulan pada 2025. Ini jadi sinyal awal pembalikan tren deindustrialisasi dan peluang menuju reindustrialisasi.
• Kontribusi dan Penyerapan Tenaga Kerja Menguat
Kontribusi sektor ini ke PDB tetap terbesar dan mulai naik, serta menyerap tenaga kerja besar. Jika momentum terjaga, sektor ini bisa kembali menjadi motor pertumbuhan dan penopang ekspor.
• Peluang dan Tantangan Reindustrialisasi
Peluang muncul dari investasi yang pulih, hilirisasi SDA, dan kebijakan pendukung. Tantangan utama ada pada regulasi, infrastruktur, teknologi, dan kebutuhan SDM.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Kinerja industri pengolahan (manufaktur) memberikan sinyal makin bergairah. Untuk pertama kali dalam 14 tahun terakhir, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan kinerja ekonomi nasional selama dua triwulan beruntun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan dua dan tiga tahun 2025, perekonomian Indonesia tumbuh masing-masing sekitar 5,12% dan 5,04% secara tahunan (year-on-year, yoy). Di periode yang sama, industri pengolahan tumbuh masing-masing 5,68% dan 5,54% yoy.
Terakhir kali pertumbuhan industri pengolahan lebih tinggi melampaui kinerja perekonomian nasional dalam dua triwulan berturut-turut seperti itu, terjadi pada triwulan tiga dan empat tahun 2011. Ketika itu, industri pengolahan tumbuh 7,14% dan 7,00%.
Meski masih terlalu dini dan angkanya tidak terlalu besar, pertumbuhan industri pengolahan pada dua triwulan beruntun ini menyalakan sinyal penting. Momentum tersebut diharapkan menjadi pertanda lahirnya re-industrialisasi.
Karena itu, peluang ini perlu dirawat. Sektor industri pengolahan memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Sejak beberapa dekade terakhir, sektor tersebut secara konsisten menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sekaligus berperan sebagai lokomotif penyerapan tenaga kerja, pendorong ekspor, dan penguatan basis pajak negara.
Fokus utama publikasi NEXT Indonesia Center kali ini adalah dinamika kinerja industri pengolahan dibandingkan PDB. Kemudian, kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta peran pentingnya agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Reindustrialisasi untuk Dorong Perekonomian
Industri pengolahan memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Sejak beberapa dekade terakhir, sektor ini secara konsisten menjadi salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sekaligus berperan sebagai lokomotif penyerapan tenaga kerja, pendorong ekspor, dan penguatan basis pajak negara.
Namun, dalam dua dekade terakhir, Indonesia juga menghadapi fenomena yang kerap disebut sebagai deindustrialisasi dini (premature deindustrialization), ketika kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB cenderung menurun sebelum negara mencapai tingkat pendapatan tinggi. Deindustrialisasi bisa membuat perekonomian Indonesia sulit keluar dari middle income trap, yakni kondisi suatu negara berhasil mencapai status pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk naik ke status pendapatan tinggi.
Kondisi tersebut memacu pemerintah untuk mendorong agenda hilirisasi sumber daya alam, reindustrialisasi, dan penguatan basis manufaktur nasional. Hilirisasi mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, penguatan industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta industri kimia dan logam dasar, merupakan bagian dari upaya menggeser struktur ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju komoditas olahan bernilai tambah tinggi.
Dalam kerangka tersebut, kinerja sektor industri pengolahan pada beberapa triwulan terakhir memberikan sinyal positif: Indonesia mulai memasuki fase pembalikan deindustrialisasi dan pemulihan peran sektor manufaktur.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) di atas menunjukkan tren kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sejak era 1960-an. Perannya cenderung menurun dari kisaran 23–24% di awal 2010-an menjadi sekitar 19–20% dalam beberapa tahun terakhir.
Sektor ini pun bergerak relatif terhadap pertumbuhan PDB nasional. Saat sektor industri pengolahan tumbuh tinggi, perekonomian nasional juga tumbuh relatif tinggi.
Bahkan hingga triwulan III-2025, mengutip data BPS, struktur PDB Indonesia masih didominasi oleh lima lapangan usaha utama. Industri pengolahan ada di posisi teratas, lantas disusul oleh (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) konstruksi; dan (5) pertambangan dan penggalian.
Di antara lima lapangan usaha tersebut, industri pengolahan menempati posisi pertama sebagai penyumbang terbesar PDB. Karena itu, terlalu naif jika perannya harus diabaikan.
Pada triwulan II-2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat 19,51%. Triwulan berikutnya, sumbangannya meningkat jadi 19,93%.
Kenaikan peran tersebut, meskipun tidak terlalu besar secara persentase, menjadi penting lantaran memberikan harapan segar setelah sempat lesu. Hal itu menunjukkan bahwa peran industri pengolahan sebagai tulang punggung dan motor pertumbuhan ekonomi nasional belum tergantikan.
Stabilitas kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, terutama usai pandemi Covid-19 tahun 2022, dapat dibaca sebagai indikasi terbukanya peluang reindustrialisasi apabila didukung oleh kebijakan yang tepat. Dengan pangsa sekitar seperlima PDB nasional dan keterkaitan ke belakang (backward linkages)2 maupun ke depan (forward linkages)3 yang kuat ke sektor lain—mulai dari pertanian (bahan baku agroindustri), pertambangan (bahan baku hilirisasi mineral), transportasi dan pergudangan (logistik), hingga jasa keuangan—industri pengolahan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan.
2. Keterkaitan antara suatu industri atau sektor ekonomi dengan industri atau sektor lain yang menjadi pemasok bahan bakunya.
3. Hubungan ekonomi di mana sektor produksi menyediakan input (bahan baku) untuk sektor produksi lainnya.
Mengingat perannya yang begitu penting, setiap perubahan pada industri pengolahan, kinerja perekonomian nasional bakal terseret. Bahkan, selain kontribusinya yang besar terhadap PDB, peran penting industri pengolahan juga tampak pada serapan tenaga kerjanya, terutama yang berpendidikan menengah.
Penguatan pertumbuhan industri pengolahan berpotensi menekan pengangguran terbuka dan meningkatkan kualitas pekerjaan, terutama jika diiringi kebijakan peningkatan keterampilan (upskilling) dan penataan hubungan industrial. Stabilitas sosial-ekonomi yang lahir dari pasar tenaga kerja yang lebih sehat berkontribusi pada stabilitas makro secara lebih luas.
Grafik di atas menunjukkan bahwa tren serapan tenaga kerja industri pengolahan cenderung naik setiap tahun. Data BPS per Agustus 2025 mencatat, jumlah pekerja yang terserap industri pengolahan mencapai 13,86% dari total 146,5 juta pekerja di seluruh Indonesia pada bulan tersebut.
Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja sektor tersebut berada dalam posisi tiga besar penyumbang serapan tenaga kerja terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (41,3 juta pekerja) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (27,5 juta pekerja). Porsi serapan tenaga kerja ketiga sektor terbesar itu mencapai 60,74% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Indeks Manufaktur Bank Indonesia dan S&P Global
Indikator kinerja sektor manufaktur dikembangkan dengan tujuan untuk mengukur performa dan arah pergerakan sektor industri pengolahan yang ada di suatu wilayah, apakah sedang ekspansi atau kontraksi. Di Indonesia, dua indeks yang umum dipakai adalah PMI (Purchasing Manager’s Index) Manufaktur S&P Global dan PMI (Prompt Manufacturing Index) Bank Indonesia (PMI-BI).
PMI S&P Global dirilis setiap bulan dan berbasis survei kepada manajer pembelian di berbagai perusahaan, sehingga sangat cepat menangkap perubahan sentimen pasar dan kondisi permintaan jangka pendek. Karakter ini membuatnya lebih sensitif dan fluktuatif, sehingga sering digunakan analis, pelaku pasar, dan investor sebagai indikator dini aktivitas manufaktur.
Sebaliknya, PMI-BI disusun setiap triwulan dan menitikberatkan pada indikator aktivitas produksi aktual, seperti volume output, utilitas kapasitas, dan kondisi tenaga kerja. Dengan responden yang lebih stabil dan fokus yang lebih struktural, PMI-BI memberi gambaran yang lebih konsisten mengenai kondisi riil sektor manufaktur nasional.
Perbedaan pendekatan dan frekuensi inilah yang membuat keduanya saling melengkapi, memberikan perspektif yang lebih utuh mengenai kesehatan sektor industri Indonesia.
Menghindari Jebakan Negara Kelas Menengah
Middle-income trap mengacu pada kondisi ketika sebuah negara berhasil mencapai status pendapatan menengah, namun kesulitan naik tangga selanjutnya: menjadi negara berpendapatan tinggi.
Banyak negara berkembang mampu lepas dari kategori pendapatan rendah, kemudian naik ke menengah usai Perang Dunia II. Sayangnya, hanya sedikit yang berhasil menembus kategori negara maju. Secara historis, dari 101 negara berpendapatan menengah tahun 1960, hanya 13 yang berhasil masuk kelompok negara berpendapatan tinggi pada 2008, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Singapura4. Selebihnya, cenderung bertahan di kelas menengah.
4. World Bank & Development Research Center (DRC) of China. China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society. Washington, DC: World Bank, 2013.
Menurut Bank Dunia, sulitnya naik kelas itu lantaran di saat pendapatan masih rendah, pertumbuhan pesat umumnya didorong oleh keunggulan tenaga kerja murah dan adopsi teknologi dari luar. Dalam fase tersebut, produktivitas nasional terdongkrak oleh peralihan sumber daya (terutama tenaga kerja) dari sektor tradisional dengan produktivitas rendah seperti pertanian ke sektor manufaktur modern yang produktivitasnya jauh lebih tinggi.
Namun, saat negara mencapai tingkat pendapatan menengah, keunggulan upah rendah mulai memudar seiring naiknya biaya tenaga kerja. Sumber pertumbuhan lama, seperti tenaga kerja murah dan teknologi impor, akhirnya tergerus. Sementara, daya saing ekspor berbasis upah murah makin uzur alias menurun.
Jika negara gagal beralih menuju sumber pertumbuhan baru berbasis inovasi dan peningkatan nilai tambah, ekonominya rentan terjebak di tingkat menengah tanpa mampu bersaing menuju level maju. Fenomena ini menjelaskan mengapa Amerika Latin dan Timur Tengah misalnya, telah berpuluh tahun berada di kelas menengah sejak 1960-an tanpa lonjakan ke kelas atas.
Jalan terbaik untuk menembus hambatan middle income trap ini adalah penguatan industri pengolahan (manufaktur). Ada sejumlah alasannya. Pertama, peralihan tenaga kerja dari pertanian ke manufaktur menghasilkan lonjakan produktivitas yang signifikan bagi perekonomian. Oleh karena itu, industrialisasi dapat mendorong pertumbuhan PDB per kapita lebih cepat.
Kedua, hasil penelitian ekonom Turki, Dani Rodrik, dalam working paper berjudul “Unconditional Convergence”5 menunjukkan bahwa sektor manufaktur di negara berkembang cenderung mengalami kenaikan produktivitas secara otomatis tanpa tergantung pada kondisi institusional atau kebijakan tertentu. Hal ini menjadikan manufaktur sebagai mesin catch-up (pengejar) ketertinggalan teknologi negara menengah dengan memperluas basis industri mereka.
5. Dani Rodrik. “Unconditional Convergence.” NBER Working Paper No. 17546, 2011.
Kemudian, negara-negara yang lolos dari middle-income trap umumnya berhasil melakukan diversifikasi ekonomi ke produk manufaktur yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Keberhasilan industrialisasi Korea Selatan6 bisa menjadi salah satu contoh baik. Diversifikasi industri dan ekspor manufaktur berteknologi tinggi ini meningkatkan kapabilitas ekonomi, mendorong inovasi lokal, dan membuka peluang pertumbuhan jangka panjang.
6. Analisis keberhasilan Korea Selatan dapat dibaca pada: Jesus Felipe, Arnelyn Abdon, & Utsav Kumar. Tracking the Middle-Income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why? ADB Economics Working Paper No. 307, 2012.
Beragam studi terhadap keberhasilan sejumlah negara untuk lepas dari middle income trap memang menunjukkan bahwa kunci utamanya adalah penguatan sektor industri manufaktur. Oleh karena itu Indonesia perlu mencari jalan terbaik guna membalik kecenderungan deindustrialisasi prematur menjadi reindustrialisasi.
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan bertajuk “Indonesian Industrialization and Industrial Policy: Peer Learning from China’s Experiences” (Eka Puspitawati, 2020), menyarankan agar investasi industri Indonesia ditingkatkan hingga 2,8 kali lipat untuk mencapai target kontribusi manufaktur di atas 30% PDB, yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Target tersebut bisa dicapai dengan mendorong investasi domestik maupun menarik investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) di sektor manufaktur, khususnya industri berorientasi ekspor yang dapat mentransfer teknologi ke dalam negeri.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan teknologi dan inovasi; diversifikasi industri dan ekspor agar tidak tergantung pada komoditas primer; pengembangan SDM dan infrastruktur; serta pentingnya menyusun kebijakan makro yang mendukung daya saing industri. Sekadar contoh adalah menjaga stabilitas nilai tukar pada tingkat kompetitif guna mendorong ekspor.
Singkatnya, industrialisasi terbukti sebagai jalan paling andal menuju status negara maju. Hampir tak ada negara yang melonjak menjadi ekonomi berpenghasilan tinggi tanpa melalui fase industrialisasi yang kuat. Bagi Indonesia, memperkuat sektor industri manufaktur bukan saja opsi, melainkan keharusan untuk memecahkan kebuntuan pertumbuhan.
Sinyal dari Pertumbuhan Kredit
Pertumbuhan kredit investasi sektor industri pengolahan terlihat mencerminkan keyakinan dunia usaha terhadap prospek sektor tersebut. Sepanjang 2017 hingga awal 2020, tren pertumbuhannya sering berada di bawah 5% (year on year, yoy), bahkan sempat negatif atau menyusut pada 2018–2019.
Hal itu menunjukkan adanya kehati-hatian investor atau bahkan perlambatan permintaan terhadap pembiayaan investasi industri pengolahan. Rasa waswas itu kemungkinan dipicu oleh ketidakpastian global, efisiensi pascapenurunan harga komoditas, atau insentif kebijakan yang belum cukup kuat mendorong ekspansi sektor ini.
Namun, mulai pertengahan 2022 hingga 2025, data Bank Indonesia menunjukkan pemulihan yang stabil. Pertumbuhan kredit investasi industri pengolahan kembali bergerak ke arah positif dan bahkan mencatatkan pertumbuhan dua digit di beberapa bulan—termasuk Agustus dan September 2025, masing-masing 11,61% dan 11,77%.
Tren pertumbuhan tersebut menandakan adanya kebangkitan minat investasi di sektor ini, seiring perbaikan permintaan domestik, insentif pemerintah seperti supertax deduction7, serta pemulihan jaringan pasokan pasca-pandemi. Kenaikan kredit itu sangat penting, karena investasi menjadi fondasi utama bagi peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi baru, dan peningkatan daya saing manufaktur nasional.
7. Insentif pajak berupa pengurangan penghasilan yang dikenakan pajak bagi industri yang menyelenggarakan program di bidang pendidikan vokasi dan teknologi.
Dengan kredit investasi yang tumbuh positif, terutama untuk sektor industri pengolahan, ada sinyal kuat bahwa struktur ekonomi Indonesia mulai kembali menekankan penguatan sektor tradisional berorientasi nilai tambah. Bila tren ini berlanjut dan dibarengi dengan kebijakan industri yang progresif, maka sektor manufaktur berpotensi kembali menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional dan menggerakkan proses industrialisasi yang sempat melambat dalam satu dekade terakhir.
Menjawab Tantangan Sektor Manufaktur
Sektor manufaktur memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik jangka menengah maupun panjang, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan nilai tambah nasional. Investasi pada sektor ini pun belakangan tampak mulai kembali tumbuh. Guna menjaga momentum pertumbuhan tersebut diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dan konsisten agar arus investasi ke sektor manufaktur terjaga, bahkan meningkat.
Sebagai langkah awal, tak berlebihan jika pemerintah menengok ulang perbaikan iklim regulasi dan kepastian usaha. Investasi jangka panjang di sektor industri sangat bergantung pada stabilitas aturan dan efisiensi birokrasi. Pemerintah perlu menyederhanakan izin usaha, menertibkan regulasi yang tumpang tindih, serta memastikan konsistensi kebijakan fiskal, ketenagakerjaan, dan perdagangan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga krusial agar implementasi di lapangan tidak menghambat realisasi investasi.
Insentif investasi juga perlu diperluas dan dipertajam. Insentif fiskal seperti supertax deduction sebaiknya diarahkan secara lebih agresif kepada sektor industri strategis, seperti manufaktur berorientasi ekspor, berbasis teknologi, atau yang aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), serta pelatihan vokasi. Pemerintah juga bisa memberi insentif bagi pelaku industri yang melakukan diversifikasi produk dan memperluas rantai pasok domestik.
Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung merupakan syarat utama agar biaya logistik dan produksi dapat ditekan. Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, pasokan energi, dan jaringan logistik akan meningkatkan daya saing manufaktur nasional. Pembangunan kawasan industri di luar Jawa perlu dipercepat dengan skema pembiayaan campuran, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Akses pembiayaan bagi investasi manufaktur juga perlu diperluas. Pemerintah dapat meningkatkan penjaminan kredit, sekaligus mendorong bank nasional dan swasta untuk lebih aktif menyalurkan kredit investasi. Untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), pendekatan klaster8 dapat menjadi solusi untuk mempercepat agregasi pembiayaan dan pembangunan ekosistem industri.
8. Sistem koordinasi yang mengelompokkan berbagai lembaga dan organisasi berdasarkan gugus kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan industri.
Terakhir, pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi menjadi fondasi jangka panjang bagi industri yang tangguh. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri serta mendorong kolaborasi riset antara dunia usaha, universitas, dan lembaga litbang. Insentif untuk transformasi digital dan adopsi teknologi hijau juga harus diperluas, termasuk untuk manufaktur berskala menengah.
Jika langkah-langkah itu dapat dilaksanakan secara konsisten, sektor manufaktur Indonesia dapat terus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi, sekaligus penggerak transformasi struktural. Dengan investasi yang meningkat, manufaktur nasional akan lebih siap menghadapi persaingan global, menyerap lebih banyak tenaga kerja produktif, dan membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah menuju status negara maju.